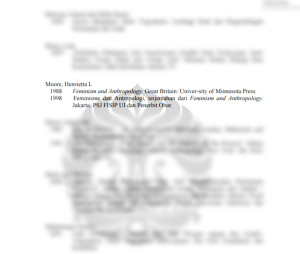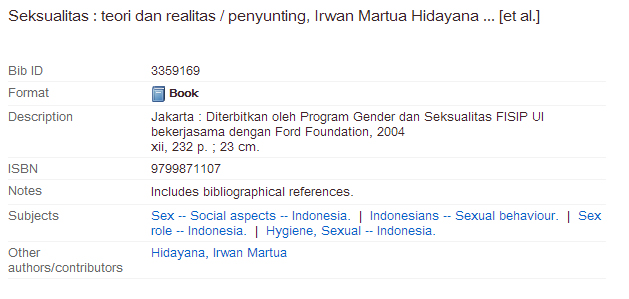Oleh: Sabina Puspita
Ditulis oleh penyintas pelecehan seksual. Penyintas mengalami sendiri pelecehan seksual di mobil antar jemput sekolah (usia 9 tahun), rumah sendiri (usia 11 dan 15), bus umum (usia 16 sampai 19 dan paling sering), lapangan basket sekolah (usia 17), rumah teman kuliah (usia 20), gedung kantor (usia 24), dan jalanan (terlalu sering atau sepanjang hidupnya di Jakarta). Pelaku setiap kejadian laki-laki dewasa. Penyintas mencatat setiap kejadian karena saat pencatatan tidak tahu harus berbuat apa atau berbicara kepada siapa.
Pandemi global COVID19 yang tengah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, berdampak besar terhadap rutinitas warga masyarakat. Dampak terbesar paling dirasakan oleh warga yang terdeteksi positif, pasien sakit lainnya, dan para tenaga medis beserta keluarga ketiga kelompok itu. Warga yang tidak terdeteksi positif dan tidak sedang sakit pun harus beradaptasi secara signifikan karena, selain tempat dan jam kerjanya berubah, pemasukannya pun mengalami penurunan bahkan terhentikan. Belum lagi dampak psikologis warga dari upaya-upaya mereka memahami ketidakpastian ini, strategi untuk bertahan hidup, dan kemampuan melindungi anggota keluarga dan orang-orang terdekat. Meskipun demikian, saya optimis bahwa vaksin itu akan tiba dan warga akan sehat kembali. Ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi modern sanggup memecahkan permasalahan pandemi ini.
Namun, tingkat optimisme saya ini terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia nil. Saat rutinitas warga kembali lagi seperti normal karena permasalahan pandemi ini pun terpecahkan, penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang tersendat karena kedaruratan COVID19 pun bisa-bisa kembali normal: birokratis, pembebanan bukti pada korban, dan berakhir dengan hukuman yang tajam bagi korban tapi tumpul bagi pelaku.[i] Ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi modern sepertinya tidak akan bisa memecahkan permasalahan satu jenis wabah yang terpendam selama ini: pembiaran kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Beberapa hal dari pandemi COVID19 memicu ide-ide terkait “praktik ideal” penanganan pelecehan seksual yang layak di perguruan tinggi. Pada tulisan ini, saya akan mencoba mengembangkan daya kreativitas saya yang didasari oleh konsumsi bacaan saya dari ilmu sosial dan politik dan pemberitaan di media, serta pengamatan saya selama melakukan riset di beberapa lapangan penelitian tahun ini.
Bukan Penyakit yang Asimtomatik
Permasalahan kekerasan seksual di Indonesia jelas sudah memasuki fase mengkhawatirkan. Sebuah survei tahun 2017 menyebutkan kota Jakarta salah satu dari 10 kota di dunia yang paling tidak aman bagi perempuan, terutama karena tingkat kekerasan seksualnya (Gambar 1). Survei lain di tahun 2018 membuktikan Indonesia adalah tempat yang paling berbahaya ke-3 di Asia Pasifik untuk perempuan bisa hidup, setelah India dan Filipina (Gambar 2).
Terutama di konteks perguruan tinggi, data kuantitatif[ii] yang mengindikasikan rendahnya jumlah laporan namun data kualitatif[iii] yang menggambarkan ragam bentuk kekerasan seksual secara detil dan nyata, jelas menunjukkan bahwa kejadian kekerasan seksual yang endemik di lingkungan akademik Indonesia bisa menjadi epidemi atau wabah tersendiri.[iv] Banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi “lazim” terjadi di konteks masyarakat yang “menormalisasi” dominasi laki-laki dan domestifikasi perempuan[v] serta tingkat kekerasannya secara umum tinggi.[vi] Padahal, satu tindakan kekerasan seksual bisa menimbulkan efek riak pada: 1) korban dan keluarganya; 2) keluarga dan kerabat pelaku; dan 3) komunitas perguruan tinggi terkait.[vii] Maka, kasus kekerasan seksual “sekecil” apa pun (Tabel 1), layak dan pantas mendapatkan respon penanganan yang serius oleh masyarakat, perguruan tinggi, dan negara, selayaknya kita menangani kasus-kasus COVID19 saat ini.

Gambar 1. Jakarta menempati peringkat ke-7 dunia sebagai tempat di mana perempuan tidak bisa hidup aman dari kekerasan seksual (Thompson Reuters Foundation dan CNN Indonesia).

Gambar 2. Indonesia menempati posisi teratas di Asia Tenggara sebagai tempat yang paling tidak aman bagi perempuan ValueChampion Singapura; The Asean Post; dan The Jakarta Post).
Penanganan yang Layak
Apabila kita terus abai dalam menanggapi gejala-gejala dan kejadian kekerasaan seksual yang selama ini endemik di masyarakat dan lingkungan akademik kita, kekerasan seksual lama-lama bisa jadi sebuah wabah atau epidemi. Maka, ibarat pengidap COVID19 ringan yang harus dikarantina minimal 14 hari, pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi seharusnya, selain dikeluarkan dari—dan dilarang masuk kembali ke—dunia akademik, dikarantinakan selama minimal 14 tahun. Karantina bisa dalam rumah aman atau lembaga pemasyarakatan, intinya pelaku harus melalui isolasi panjang dari kehidupan bermasyarakat (extreme social distancing). Namun, berbalik dengan pengidap COVID19, identitas pelaku diinformasikan ke masyarakat. Selama karantina, pelaku menerima “perawatan instensif” berupa pendidikan soal relasi kuasa dan gender. Negara[viii] perlu melengkapi tenaga kerja yang menyampaikan materi pendidikan ini dengan alat pelindung diri atau APD yang memadai, sebab kita tidak tahu apa yang pelaku dapat perbuat padanya. Hukuman bagi pelaku bisa berkurang dengan pembuktian laju perkembangan nilai, pemahaman, dan perilaku pelaku terkait bagaimana memperlakukan sesamanya dengan adil dan beradab. Pembuktian ini harus dibuat serumit dan semenyakitkan mungkin—serumit dan menyakitkan proses pembuktian yang dibebankan pada korban kekerasan seksual (burden of proof) waktu melaporkan tindakan pelakunya ke pihak-pihak berwenang di kehidupan nyata saat ini. Terlebih dari itu, aset pelaku dibekukan negara dan pelaku harus bekerja tanpa upah untuk negara, sebagai ganti rugi ongkos negara membiayai pendidikannya semasa karantina.
Bagi pihak-pihak berkuasa yang terbukti lalai dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk berupaya membungkam korban, saksi, dan pendampingnya (hostile environment sexual harassment),[ix] negara harus memperlakukan mereka seperti “pasien dalam pengawasan” atau PDP. Dalam hal ini, PDP dikarantina dari kehidupan bermasyarakat minimal 14 minggu, dan menerima pendidikan soal relasi kuasa dan gender juga selama itu. Negara berhak memberlakukan denda pada PDP untuk ongkos pendidikan yang mereka terima semasa karantina. Setelah masa karantina, kegiatan ekonomi dan bersosialisasi PDP dibatasi. Selain itu, PDP wajib melakukan pelaporan diri berkala hingga waktu yang tidak ditentukan, dengan mengikuti sejumlah tes yang relevan. Untuk bisa lepas dari status PDP, persyaratannya birokratis—sebirokratis proses penanganan laporan korban kekersan seksual di kehidupan nyata saat ini. Hal ini diperlukan untuk memastikan PDP sembuh total, sehingga mereka tidak mengulangi kelalaiannya dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mereka.
Korban kekerasan seksual seharusnya mendapat perlakuan layaknya masyarakat dunia sekarang memandang tenaga medis COVID19 sebagai barisan terbelakang pertahanan kemanusiaan (last defense line), kampus harusnya jadi barisan depannya (frontline).[x] Mengapa? Sebab kampus seharusnya tidak mempertaruhkan nyawa anggota sivitas akademikanya yang jadi korban kekerasan seksual untuk mengidentifikasi keberadaan pelaku kekerasan seksual di lingkungan yang seharusnya aman bagi seluruh anggota sivitas akademika, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ekspresi gender, seksualitas, suku, ras, dan agama. Setiap korban sudah dihadapkanpada resiko: 1) dikucilkan orang sekitar; 2) terhambat proses belajarnya; dan 3) depresi karena harus mengingat kembali kronologi dan trauma pelecehan seksual yang ia alami.[xi] Oleh karena itu, hak-hak korban sebagai manusia harus dipulihkan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya—dan perguruan tinggi serta negara mempertanggungjawabkan kelalaiannya—setidaknya dengan membiayai beban finansial yang korban tanggung untuk pemulihannya.
Penutup
Pendekatan dan metode
yang penulis ajukan ini memang belum dapat dibuktikan secara ilmiah
keberhasilannya. Namun, apakah kita harus menunggu keseriusan isu kekerasan
seksual di perguruan-perguruan tinggi Indonesia menjadi sebuah pandemi dulu,
baru mencobanya? Ibarat pandemi yang menuntut warga masyarakat untuk mengubah
pola hidup secara signifikan demi pembasmian virus mematikan, maka masyarakat
pun harus mulai mengubah pandangannya dan memperlakukan juga segala perilaku
dan pelaku kekerasan seksual sebagai sesuatu yang mematikan kesempatan hidup orang
lain dan harus dibasmi. Semoga ada pihak-pihak berkuasa yang bersedia serius
memikirkan (atau mungkin mengadopsi) pendekatan dan metode seutopis ide-ide
yang ditawarkan tulisan ini.
Catatan Penulis
[i] Baca reportase dari lembaga-lembaga pers mahasiswa seperti “Di Bawah Cengkraman Dosen Mesum” (LPM Humanika IAIN Gorontalo) dan “Keberlanjutan Kasus Agni” (Balairung Press) untuk contoh-contoh kasus di lingkungan pendidikan tinggi; baca juga “Divonis 10 Bulan Penjara karena Lecehkan 5 Siswi” untuk contoh kasus di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.
[ii] Lihat model yang dibangun Tirto berdasarkan 174 testimoni penyintas untuk proyek #NamaBaikKampus; baca juga Ardi dan Muis (2014) yang menemukan 40% dari 304 mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi; dan Rusyidi, Bintari, dan Wibowo (2019) untuk mehami keterkaitan antara pengalaman dan pengetahuan tentang kekerasan seksual mahasiswa perguruan tinggi Indonesia melalui metode kuantitatif.
[iii] Baca “Predator Seksual di Kampus” (Ghaliyah 2019); Widyasari dan Aryastami (2018) untuk konteks mahasiswa berpacaran di Yogyakarta; dan Artaria (2002) untuk konteks mahasiwa di Surabaya.
[iv] Paludi et al. (2006) menyebut fenomena kekerasan seksual dalam kampus di berbagai negara sebagai The Sound of Silence atau “suara lantang kesunyian.”
[v] Menurut survei yang dilakukan di kalangan mahasiswa Republik Rakyat Tiongkok, sebagian besar mahasiswa tidak menganggap perilaku seksis dan misoginis sebagai bentuk intimidasi, diskriminasi atau pelecehan seksual (Tang et al. 1995).
[vi] Menurut sebuah kajian perbandingan mancanegara, mahasiswa dalam konteks masyarakat demikian harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkala dulu untuk dapat mengenali bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual (Paludi et al. 2006); dan di konteks Indonesia, mereka yang belum pernah mengalami langsung kekerasan seksual cenderung tidak bisa mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual (Rusyidi, Bintari, dan Wibowo 2019).
[vii] Koss et al. (2014)
[viii] Maksud “negara” di sini adalah kementerian dan lembaga nasional terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (apabila pelaku itu Aparat Sipil Negara), dan sebagainya.
[ix] Di konteks Amerika Serikat, keadaan terjadinya kekerasan seksual di kampus bisa digolongkan menjadi dua, yakni, quid pro quo atau hostile environment; golongan pertama merujuk pada keadaan di mana korban dilecehkan karena tekanan atau ancaman dari pelaku yang sifatnya transaksional, dan golongan kedua merujuk pada kasus di mana korban dilecehkan karena lingkungan perguruan tingginya yang tidak mendukung atau malah memungkinkan terjadinya kekerasan seksual (Paludi et al. 2019).
[x] Lihat cuplikan video pernyataan Dr. Michelle Au.
[xi] Baca Artaria (2002) untuk memahami bagaimana pengalaman kekerasan seksual pada mahasiswa korban berdampak pada rambutnya yang rontok dan depresi berat; Jackson (2018) untuk dampak lain kekerasan seksual dalam konteks Amerika Serikat; Paludi et al. (2006) dalam konteks negara-negara Latin Amerika dan Afrika; dan Fairbairn (2015) dalam konteks dunia maya.
Daftar Pustaka
Artaria, M. D. (2002). Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer.
Ardi, N. M. S., & Muis, T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Unesa, 4(3).
Fairbairn, J. (2015). Rape threats and revenge porn: Defining sexual violence in the digital age. University of Ottawa Press: EGirls, ECitizens, 229-252.
Fitzgerald, L. F., Magley, V. J., Drasgow, F., & Waldo, C. R. (1999). Measuring sexual harassment in the military: The sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD). Military Psychology, 11, 243–263.
Jackson, M. D. C. (2018). Litigation and the Title IX Coordinator: A Look Into the Effects of Litigation on the 23 CSU System Campuses after Implementation of a Title IX Coordinator (Doctoral dissertation, California Baptist University).
Koss, M. P., Wilgus, J. K., & Williamsen, K. M. (2014). Campus sexual misconduct: Restorative justice approaches to enhance compliance with Title IX guidance. Trauma, Violence, & Abuse, 15(3), 242-257.
Paludi, M., Nydegger, R., DeSouza, E., Nydegger, L., & Dicker, K. A. (2006). International perspectives on sexual harassment of college students: the sounds of silence.
Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Share: Social Work Journal, 9(1), 75-85.
Tang, C. S. K., Yik, M. S., Cheung, F. M., Choi, P. K., & Au, K. C. (1995). How do Chinese college students define sexual harassment? Journal of Interpersonal Violence, 10(4), 503-515.
Widyasari, R., & Aryastami, N. K. (2018). Kajian Sosiologis Perilaku Beresiko Kesehatan Pada Kekerasan Dalam Berpacaran Mahasiswa Di Yogyakarta. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(1), 48-59.