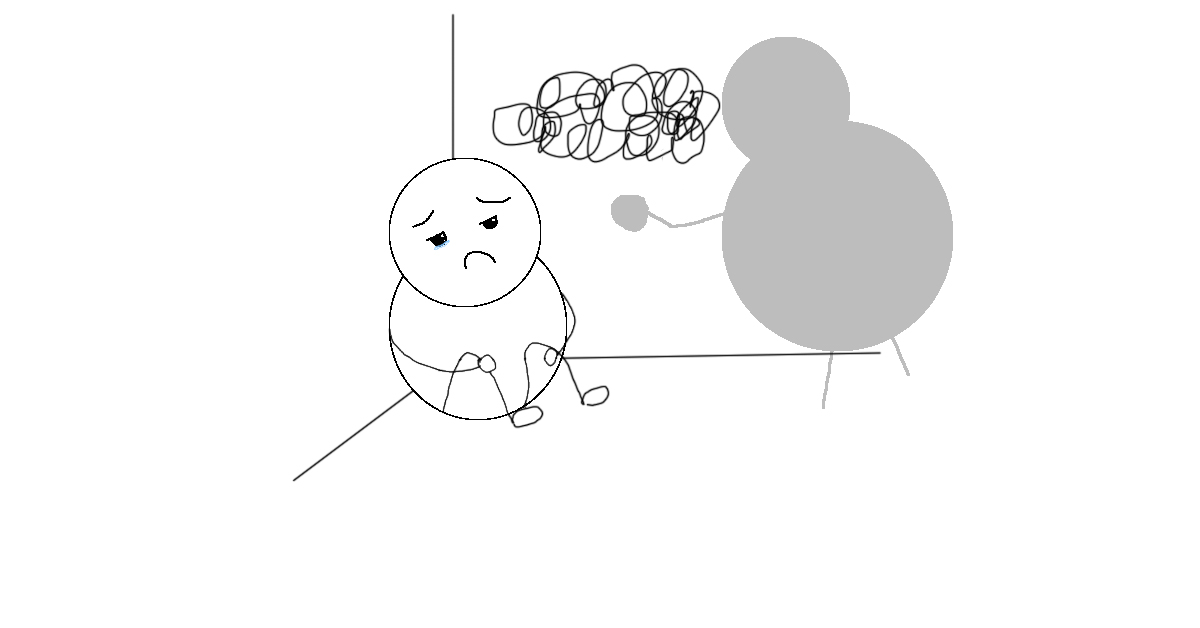Oleh: Reni Kartikawati
Indonesia masih dikejutkan dengan angka kasus kekerasan pada anak yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020, telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual (www.kemenpppa.go.id). Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan data tahun 2019 sebanyak 1.192 kasus laporan (https://jabar.idntimes.com). Lebih lanjut, berdasarkan hasil laporan Wahana Visi Indonesia tahun 2020, mengenai “Pandemic Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap Anak Indonesia” menyebutkan bahwa hampir dua pertiga anak mengaku justru mengalami kekerasan verbal dari orang tuanya (61,5%), dan anak mengaku mengalami kekerasan fisik (11,3%), saat harus belajar di rumah atau work from home ‘WFH’ (https://www.wahanavisi.org/).
Melihat angka kasus kekerasan pada anak yang semakin meningkat setiap tahunnya, pencegahan kekerasan pada anak menjadi hal yang harus lakukan dengan serius oleh pemerintah, seluruh elemen masyarakat, dan tidak terkecuali, institusi keluarga. Pada masa pandemi Covid-19, keberadaan anak di dalam rumah, tidak serta merta membuat anak berada pada ‘ruang aman’. Rumah sebagai tempat yang seharusnya ‘aman’ untuk anak justru menjadi rentan di masa pandemi. Menurut Kemen PPPA, rumah tangga menjadi rentan karena banyaknya anggota keluarga yang harus tinggal di rumah dalam waktu yang lama, yang pada saat bersamaan menghadapi pula masalah pola pengasuhan, serta masalah ekonomi akibat kehilangan penghasilan, menjadi beberapa penyebab tingginya angka kasus kekerasan pada anak di masa pandemi (www.kemenpppa.go.id). Namun, apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan sehingga kasus kekerasan pada anak justru semakin tinggi di masa pandemi covid-19?
Anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan (vulnerability of child become victim), sehingga harus dilindungi. Dalam perspektif perlindungan anak, khususnya pada UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitu, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperan dalam upaya perlindungan anak disebutkan pada Pasal 20, yaitu “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sementara itu, definisi kekerasan pada anak menurut WHO, yaitu “suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dan dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.” Dengan kata lain, pelaku kekerasan terhadap anak biasanya memiliki ‘relasi kuasa’ dan hubungan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak tersebut berada. Tidak terkecuali rumah dalam hal ini ‘keluarga’ atau orang dewasa lainnya yang dapat juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.
Jika melihat dari data laporan WVI tahun 2020, serta laporan Kemen PPPA, mengenai penyebab kasus kekerasan pada anak di rumah saat masa pandemic Covid-19, seperti adanya pengaruh depresi yang dialami orang tua akibat pandemic, menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya kekerasan pada anak, sebagai bentuk pelampiasan tidaklah dapat dibenarkan. Orang tua yang memiliki hak kuasa atas pengasuhan pada anak adalah orang yang harusnya mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya (Pasal 1, point 11 UUD Perlindungan Anak).” Artinya tugas orang tua adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan penjabaran tersebut, anak sebagai korban dijadikan target sasaran orang tua atau orang yang lebih dewasa dari dirinya karena posisinya yang lemah. Adanya pandemic Covid-19 yang membuat anak selalu berada di rumah juga sekaligus membuka peluang bagi para pelaku kekerasan untuk melampiaskan emosi sosial psikologisnya kepada anak. Hal ini juga terkait masih adanya pemikiran bahwa anak adalah ‘asset keluarga’ yang dapat diatur, dan dimiliki oleh orang tua selaku wali yang memiliki hak asuh anak secara penuh. Artinya, jika terjadi kekerasan pada anak maka orang tua/wali menganggap hal tersebut adalah bagian dari proses pengasuhan dan ranah privat rumah tangga. Dengan demikian, kontrol sosial atas bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi baik dalam bentuk verbal, fisik, sampai dengan kekerasan seksual, yang marak terjadi akhir-akhir ini di masa pandemi, terkadang sulit untuk dikontrol oleh masyarakat. Hal inilah yang harus ditindaklanjuti lebih jauh oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, serta seluruh lembaga pemerhati perlindungan anak, agar pola terjadinya kekerasan pada anak tidak selalu berulang dan baru diketahui pasca terjadinya kekerasan.
Upaya preventif atau pencegahan dengan mengedukasi keluarga sebagai unit terkecil dan terdekat dengan anak di rumah menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya bentuk-bentuk kekerasan. Begitu juga dengan element masyarakat selaku agen sosial yang dapat membantu megontrol dan melihat gejala prakekerasan yang bisa dan mungkin terjadi di lingkungan sosialnya. Karena jika kontrol sosial lemah, maka peluang terjadinya kekerasan semakin tinggi, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang membuat terbatasnya orang-orang sekitar mengetahui kondisi psikologis dan sosial anak di rumah. Terlebih, adanya batasan ranah publik dan privat sering pula dijadikan alasan komunitas tidak dapat berbuat lebih jauh ketika menemukan bentuk-bentuk atau gejala kekerasan di lingkungannya.
Untuk itu, pemerintah beserta lembaga independent (Komnas Anak, KPAI, dll) dan seluruh elemen masyarakat harus membangun sistem pemantauan kekerasan pada anak di tingkat komunitas untuk mencegah agar segala bentuk kekerasan kepada anak. Pemberian edukasi pada komunitas dan orang tua mengenai praktik pola pengasuhan positif (tanpa kekerasan), sosialisasi peran bystander/saksi di keluarga atau komunitas, serta kemampuan komunitas untuk membangun sistem rujukan dan layanan kekerasan pada anak perlu ditingkatkan kapasitasnya. Selain itu, pelibatan anak untuk memutus rantai kekerasan juga perlu diperhatikan, misalnya dengan cara memberikan edukasi sejak dini tentang apa yang menjadi hak anak, kepada siapa anak bisa melapor dan meminta perlindungan jika mengalami kekerasan. Di samping itu, pemerintah juga perlu menjamin program perlindungan anak berbasis komunitas tetap berjalan pada masa pandemi, terutama upaya pencegahan bukan semata-mata pada penanganan kasus kekerasan pada anak. Merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap anak Indonesia dari kekerasan. Perlindungan anak tidak berhenti pada diterbitkannya regulasi kebijakan saja, namun diperlukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan program yang nyata dari pemerintah untuk mewujudkan anak Indonesia bebas dari kekerasan. Selamat Hari Anak Nasional 2020!
Sumber referensi :
“Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi Kemen PPPA Sosialisasikan PProtokol Perlindungan Anak”, 23 Juli 2020, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak
“Pandemic Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap Anak Indonesia: Sebuah Penilaian Cepat Untuk Inisiasi Pemulihan Awal,” https://www.wahanavisi.org/id/media-materi/publikasi.html
“Selama 2019, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak”, https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/4