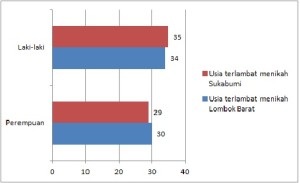Ilustrasi : R. Aji Prasetyo
Oleh : Reni Kartikawati
Perkawinan dengan mekanisme merariq (kawin lari) sejatinya harus dilihat sebagai sebuah kearifan adat yang telah menjadi suatu bagian budaya karena merupakan ritual asli dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan secara turun-temurun, termasuk di Desa Surabaya Utara, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Jika ditelusuri lebih jauh, budaya merariq pada dasarnya memiliki nilai keagamaan dan kesusilaan yang sakral, serta hingga batas tertentu dapat menekan perkawinan usia anak.
Saat ini, istilah perkawinan usia anak (merariq kodeq) menjadi hal yang dipermasalahkan, padahal pada zaman dahulu istilah tersebut tidak dikenal. Permasalahan yang terjadi adalah perubahan sosial yang turut mengubah struktur sosial masyarakat Sasak, termasuk nilai, norma, hubungan kelembagaan, serta aturan kebijakan dari pemerintah yang baru dan diseragamkan bagi setiap daerah, seperti pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 yang mengatur tentang masalah batasan usia perkawinan.[1] Hal ini secara tidak langsung menggantikan dan mendegradasi nilai-nilai kearifan lokal suku Sasak yang sudah ada, tidak terkecuali perkawinan merariq. Selain itu, aturan kebijakan nasional tersebut nyatanya tidak sesuai dan justru membuat jurang pemisah antara adat dengan kehidupan sosial yang lebih besar yang mana menurut sudut pandang kriminologi budaya, adat merariq dianggap sebagai budaya yang menyimpang (culture as crime), serta menimbulkan konflik norma tingkah laku[2] bagi masyarakat adat Sasak di Desa Surabaya Utara, tidak terkecuali pada generasi muda suku Sasak saat ini.
“Zaman dahulu sesudah masuknya agama Islam ke Lombok untuk perempuan kalau sudah menstruasi, perempuan itu boleh dikawini. Kalau sekarang ini nikah muda dianggap salah, tidak boleh dilakukan karena ada peraturan dari pemerintah..” (Wawancara Lalu IT, Wakil Ketua Majelis Adat Sasak Paer Timuq, Desa Sakra, Kab. Lombok Timur, 30 April 2016)
Pada perkembangannya, praktik merariq dalam tradisi perkawinan suku Sasak di Desa Surabaya Utara ternyata dipahami hanya sekedar ‘ritual’ praktiknya saja. Nilai-nilai budaya merariq yang dahulu ada dan terus dipertahankan perlahan-lahan mulai bergeser dari pemaknaan nilai aslinya. Perubahan tersebut nyatanya juga tidak diikuti oleh restrukturisasi kelembagaan sosial termasuk peran agen-agen sosial di dalam masyarakatnya, seperti orang tua, lembaga sosial non formal (tokoh adat/tokoh agama/tokoh masyarakat) dan lembaga formal seperti sekolah dan madrasah. Ketika peran agen sosial yang lama berubah, sementara agen sosial baru yang terbentuk belum dipersiapkan untuk menggantikan dalam mensosialisasikan nilai, norma, pengetahuan, serta kebijakan yang lebih baru, dan negara tidak hadir dalam menjaga tatanan masyarakat maka yang terjadi adalah ketidakjelasan peran kontrol sosial dalam masyarakat.
Adanya kekosongan peran agen pengendalian sosial inilah yang membawa konsekuensi logis pada munculnya persoalan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh generasi muda Sasak, tidak terkecuali anak perempuan Sasak sebagai pihak korban yang paling rentan mengalami viktimisasi struktural[3] dari akibat perkawinan usia anak melalui mekanisme merariq di Desa Surabaya Utara.
Untuk itu, diperlukan beberapa upaya bersama dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat dusun, desa, hingga kabupaten/kota dan provinsi secara lebih luas dalam mencegah dan mengakhiri perkawinan usia anak yang hingga batas tertentu mengatasnamakan adat merariq. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu :
- Merevitalisasi peran lembaga adat serta mengintegrasikannya dengan peran agen sosial untuk mensosialisasikan nilai perkawinan yang baru sesuai dengan nilai adat perkawinan merariq;
- Pemerintah sebagai leading sector berkewajiban memfasilitasi masyarakat adat termasuk para agen sosial untuk mendorong kesepakatan bersama, membuka forum dialog terkait pencegahan praktik perkawinan usia anak yang tidak bertolak belakang dengan hukum adat Sasak;
- Pemerintah membuat program nyata yang mendukung pencegahan perkawinan usia anak melalui lembaga terkait, seperti BP4 dan KUA yang sifatnya tidak menjadi agenda formalitas saja.
- Pemerintah perlu memberikan informasi pendidikan nilai adat perkawinan merariq, serta pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, termasuk dampak perkawinan usia muda kepada anak sejak dini baik secara formal melalui sekolah dan non-formal melalui forum kelembagaan agama dan daerah.
- Memastikan dan mendorong pelibatan remaja atau forum remaja di tingkat sekolah, dusun dan desa, kabupaten/kota hingga nasional untuk sama-sama mensosialisasikan program pemerintah terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang selaras dengan nilai adat masyarakat Sasak.
[1]Batasan usia perkawinan (kedewasaan) menurut UU Perkawinan dan Perlindungan Anak dilihat berdasarkan usia biologis, sementara dalam adat Sasak usia biologis bukanlah satu-satunya prasyarat kedewasaan seorang anak. Usia secara sosial seperti telah baligh, memiliki kemampuan mengerjakan pekerjaan domestik, menenun (bagi perempuan) dan mampu bekerja menghasilkan uang (bagi laki-laki).
[2]Menurut Sellin, apabila berkaitan dengan norma hukum, hukum dari suatu kebudayaan yang lebih besar diperluas yurisdiksi wilayah keberlakuannya ke wilayah kebudayaan lain (kebudayaan yang lebih kecil) dan aturan tersebut dipaksakan maka akan terjadi konflik norma tingkah laku dalam masyarakat (Sellin, 1938).
[3] Viktimisasi struktural yaitu korelasi positif antara ketidakberdayaan, kekurangan dan frekuensi korban kejahatan. Selain itu, stigmatisasi budaya dan marjinalisasi juga meningkatkan risiko korban kejahatan dengan menunjuk kelompok tertentu sebagai ‘fair game’ atau korban budaya yang sah (Fattah, 1999: 65-66).
Referensi :
Fattah, Ezzat A. (1999). Victimology Today: Recent Theoretical and Applied Developments, Resource Material Series No.56 (1999), pp. 60–70. (internet), [25 Oktober 2016]. Di unduh:
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No56/No56_09VE_Fattah2.pdf.
Kartikawati, Reni. (2016). Viktimisasi Struktural terhadap Perkawinan Adat ‘Merariq’ Pada Anak Perempuan (Studi Kasus Perkawinan Usia Anak di Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB). Tesis : Program Pasca Sarjana Kriminologi, Peminatan Perlindungan Anak, FISIP UI.
Sellin, Thorsten. (1938). Culture Conflict and Crime, American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 1 (Jul., 1938), pp. 97-103. Published by: The University of Chicago Press. (internet), [25 Oktober 2016]. Di unduh dari: http://www.jstor.org/stable/2768125.
Editor : Gabriella Devi Benedicta