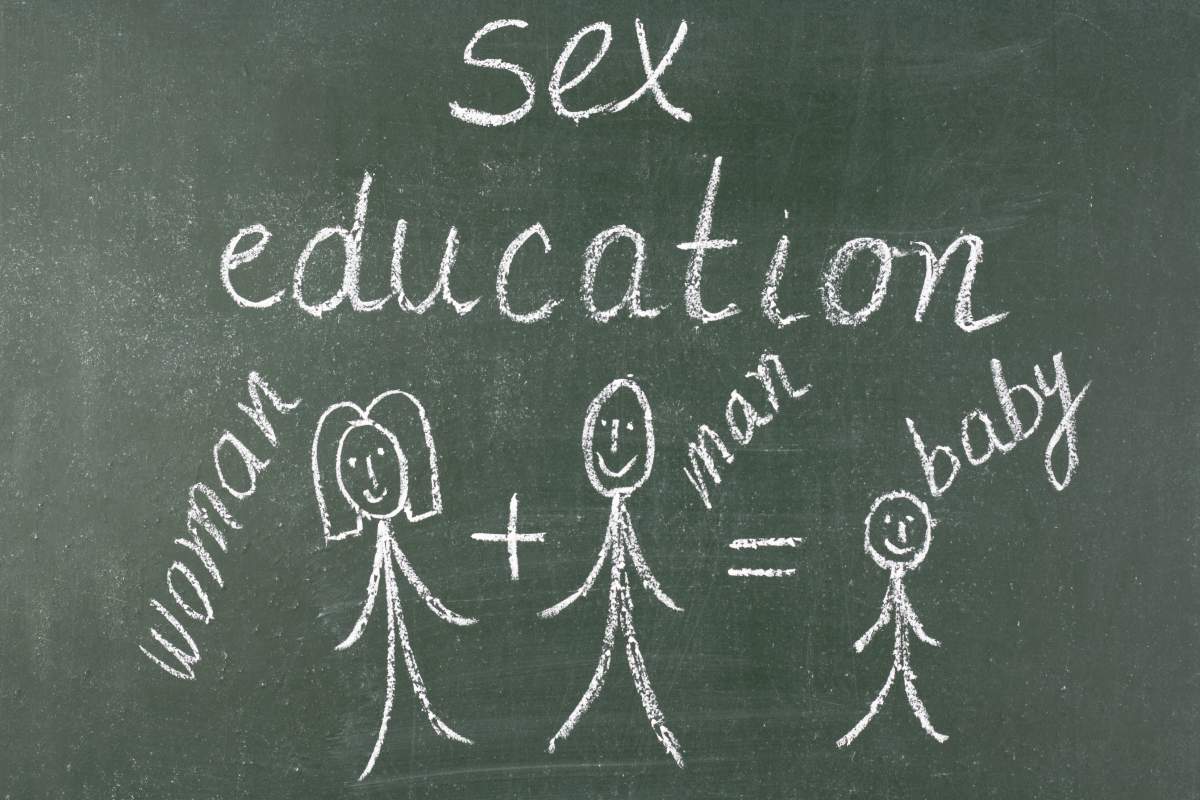Foto: Sari Damar Ratri
Oleh: Muhammad Nurun Najib (Najib)
Sudah tak asing lagi kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya. Namun banyak peneliti beranggapan bahwa, proporsi jumlah penduduk ini ternyata tidak berbanding lurus dengan perkembangan sumber daya manusianya (SDM). Jika kita melihat pada sektor kesehatan misalnya, Angka Kematian Ibu (AKI) ternyata masih menempati urutan teratas di antara negara-negara tetangga. Artikel-artikel ilmiah dan popular yang menyatakan tentang ini bisa dengan mudah di dapatkan di internet. Prakarsa, sebuah perkumpulan yang bekerja dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesejahteraan ide dan penelitian menyatakan, ada kenaikan yang signifikan atas Angka Kematian Ibu (Prakarsa, Oktober 2013)[1]. Misalnya saja hasil dari Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang menunjukkan bahwa terdapat 359 AKI di antara 100.000 kelahiran hidup. Angka ini melambung tinggi ketika dibandingkan data SDKI pada tahun 2007, di mana angkanya menunjukkan terjadi 228 kasus AKI di antara 100.000 kelahiran hidup.
Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu sebesar tiga-perempatnya pada tahun 2015. Sementara target penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar dua-pertiga. Dari kesepakat global tersebut Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi 102/100.000 Kelahiran Hidup (KH), Angka Kematian Bayi dari 68 menjadi 23/1.000 KH, dan Angka Kematian Balita 97 menjadi 32/1.000 KH pada tahun 2015[2]. Target-target tersebut nampak snagat menjanjikan, seolah-olah menciptakan pedoman bekerja yang cukup strategis. Tetapi disaat bersamaan, target capaian MDGs sesungguhnya bisa dijadikan tolak ukur kemunduran dari program pemerintah dalam menurunkan AKI di Indonesia.
Mari kita lihat kondisi saat ini, pada tahun 1997 sebenarnya Indonesia pernah ditempatkan oleh WHO sebagai negara yang berhasil dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pada tahun itu, pemerintah mampu menurunkan angka 390 kasus menjadi 334 di antara 100.000 kelahiran selama kurun waktu tiga tahun. Keberhasilan yang dicapai Indonesia pada tahun itu tidak terjadi secara instan. Dalam lembaran sejarah, satu dekade sebelumnya, yaitu pada tahun 1987 saat WHO meluncurkan Safe Motherhood Initiative, Indonesia langsung menjawabnya dengan mengadakan program Making Pregnancy Safer (MPS). Sejak saat itu pemerintah juga mencoba mengembangkan program lainnya. Salah satu program yang dikembangkan adalah tentang hak reproduksi bagi remaja melalui pelayanan konseling yang baik dan benar. Hal ini membuat Indonesia pada kurun waktu antara tahun 1980 sampai tahun 2000 terbilang sukses untuk program KIA.
Sementara itu, kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan ibu dan anak nyatanya juga sudah diatur dalam beragam regulasi yang ada. Sebagai contoh, adanya regulasi pemerintah yang mewajibkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesehatan, utamanya kesehatan ibu dan anak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2014 alokasinya hanya sebesar 248 milyar rupiah atau sekitar 0,54 persen dari total anggaran bidang kesehatan. Potret ini seharusnya bisa menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk kembali dapat memprioritaskan KIA dalam kebijkan-kebijakannya. Tidak lain tujuannya adalah untuk kembali memperbaiki kualitas KIA di Indonesia yang belum mencapai target MDGs 2015 hingga saat ini. Dengan upaya perbaikan kebijakan tentang kesehatan reproduksi, pemerintah tetap saja menilai bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual tidak perlu disedikan di tingkat sekolah. Pernyataan tersebut muncul ketika pengajuan revisi Undang-undang Sisdiknas yang diajukan oleh gugus tugas Seperlima di tolak karena dianggap kesehatan reproduksi dan seksual bukan lah isue prioritas dimana tidak ada masyarakat yang dirugikan. Kenyataan tersebut sungguh ironis, ketika para peniliti melihat bahwa AKI dan AKB bisadicapai melalui perbaikan standar pendidikan kesehatan repoduksi dan seksual.
Penyunting: Reni Kartikawati dan Sari Damar Ratri
Referensi:
[1] Saputra, Wiko. 2013. “Angka Kematian Ibu (AKI) melonjak, Indonesia Mundur 15 Tahun: Laju Penurunan Kematian Ibu di Indonesia terburuk dari Negara – Negara miskin di Asia” Prakarsa: Policy Review. Diakses dari http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Prakarsa%20Policy_Oktober_Rev3-1.pdf
[2] Kesmas, http://www.indonesian-publichealth.com/surveilans-kematian-ibu/ diakses tanggal 21 Januari 2016, pukul 14:10 WIB.