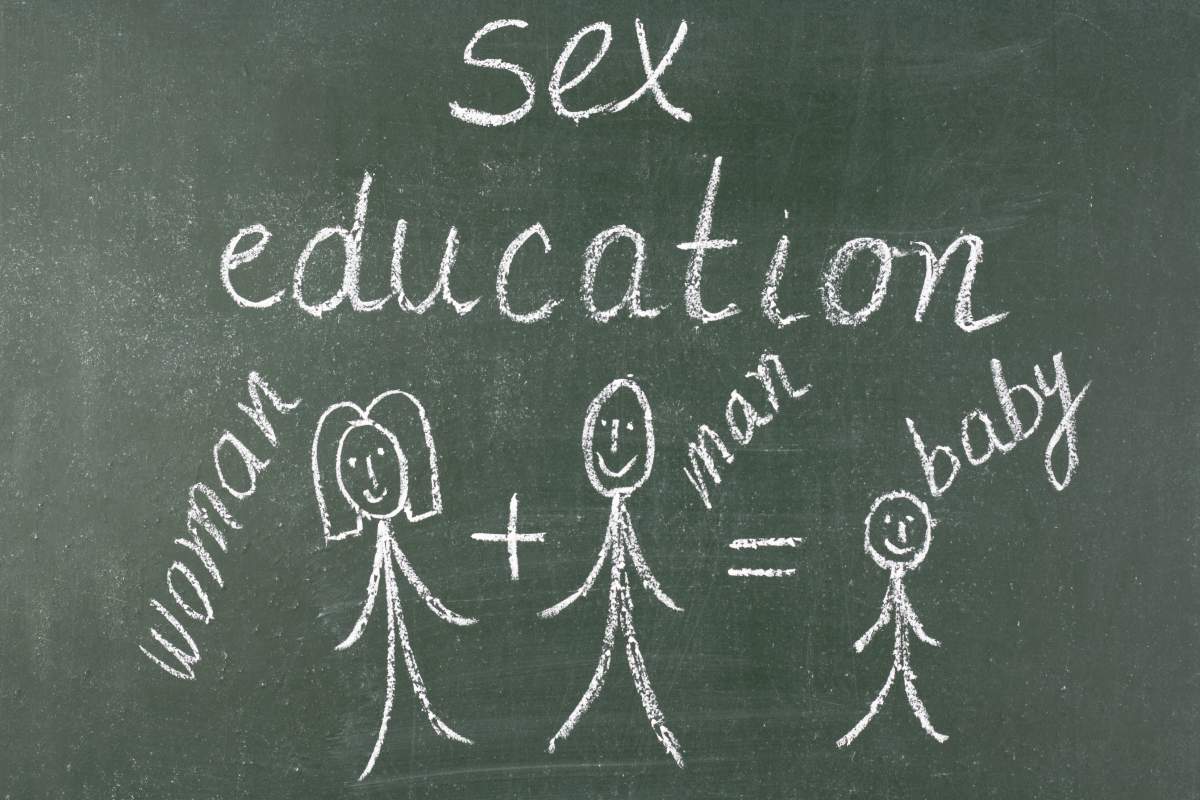Oleh : Gabriella Devi Benedicta
Diskursus mengenai isu seks, tubuh dan gender di dunia kerja semakin berkembang dan kompleks dari waktu ke waktu. Persoalan berkembang dari ketidaksetaraan antara perempuan (cisfemale) dan laki-laki (cismale)[1] yang bersifat biner, melainkan juga melibatkan juga representasi identitas lainnya, yaitu kelompok homoseksual dan transgender[2]. Di Indonesia kita mengenal dua kategorisasi transgender, yaitu waria dan trans laki-laki[3]. Dibandingkan dengan trans laki-laki, di Indonesia waria dianggap lebih dominan dalam menunjukan visibilitasnya. Tidak jarang, waria mengalami berbagai persoalan dalam dunia kerja terkait identitas dan ekspresi gender mereka. Waria, dalam hal ini mendapat diskriminasi dalam mencari pekerjaan, terutama dalam sektor formal seperti dalam pekerjaan seperti mengajar, perbankan bahkan salon menengah atas yang dianggap ‘aman’ untuk mereka.[4]
Tidak berbeda dengan waria, trans laki-laki mengalami berbagai dilema dan persoalan terkait identitas gender baru yang dibentuknya dalam dunia kerja. Memilih untuk menjadi ‘berbeda’ sebagai konsekuensi atas transisi fisik/medis maupun sosial[5] yang dilakukan berdampak terhadap pilihan kerja trans laki-laki. Berbagai persoalan dapat muncul terkait dengan identitas baru yang dipilih sebagai seorang trans laki-laki ketika mereka memasuki dunia kerja yang memiliki mekanisme dan aturan tersendiri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap enam informan kunci trans laki-laki muda usia 18-24 tahun di wilayah Jakarta dan Bekasi, peneliti mencoba mengidentifikasi dan menemukenali berbagai persoalan terkait visibilitas trans laki-laki muda atas identitas gendernya di dunia kerja.
Dalam pasal 5 UU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diatur hak bagi bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 32 dalam UU tersebut juga mengatur dengan jelas mengenai penempatan tenaga kerja yang dilaksanan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Dalam Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958 dengan jelas disebutkan larangan diskriminasi terhadap jabatan dan pekerjaan (artinya setiap pembedaan, pengabaian atau preferensi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, pencabutan kewarganegaraan atau asal muasal yang mengakibatkan lemahnya atau batalnya untuk memperoleh kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pelatihan, akses ke pekerjaan dan atau jabatan tertentu, keamanan dan kondisi terkait dengan pekerjaan).[6]
Identitas gender yang diyakini sebagai trans laki-laki memberikan pilihan untuk menunjukkan visibilitas mereka melalui ekspresi gender, baik secara terbuka maupun tertutup. Ekspresi gender yang terbuka dapat ditunjukkan melalui transisi, baik secara sosial maupun fisik. Namun, hal ini ternyata menimbulkan dilema tersendiri ketika mereka dengan terbuka menunjukkan visibilitas atas ekspresi gender mereka di dunia kerja. Persolan yang umumnya dihadapi oleh trans laki-laki muda di dunia kerja terkait dengan isu registrasi diri. Indonesia adalah salah satu negara yang dengan spesifik mencantumkan informasi atas jenis kelamin biner (perempuan dan laki-laki) dalam KTP sebagai standar informasi diri.
Negasi atas pemberian identitas gender sesuai yang tertera dalam kartu identitas diri mereka membuat salah satu informan akhirnya melakukan perubahan data diri secara ilegal (dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki). Negasi lain yang dilakukan adalah dengan menunjukkan ekspresi gender mereka sebagai laki-laki lewat penampilan dan pakaian. Hal ini menimbulkan masalah karena adanya anggapan ketidaksesuaian antara penampilan dengan data jenis kelamin yang tercantum di dalam KTP mereka. Trans laki-laki yang berpenampilan maskulin dengan kemeja, celana panjang, rambut pendek, kumis maupun jenggot serta bersuara berat menemui masalah ketika pihak perusahaan menemukan adanya perbedaan antara ekspektasi dan realitas yang tertera dalam data diri mereka di KTP sebagai perempuan.
Pakaian seperti kemeja, jas maupun celana panjang yang digunakan trans laki-laki adalah bentuk komunikasi non verbal yang digunakan untuk merepresentasi diri sebagai ‘laki-laki’. Konsepsi tubuh yang terkait dengan pakaian dapat dianggap sebagai identitas ganda signifikan, baik untuk pengguna dan untuk orang-orang yang berinteraksi dengan pengguna. Tubuh menempati posisi kunci dalam unit dasar representasi dalam karya Claude Lévi-Strauss, dimana tubuh adalah konstruksi simbolis.[7] Tubuh dibentuk dan dikendalikan oleh masyarakat. Shiling dalam bukunya The Body and Social Theory, mengungkapkan pandangan Foucault dan Goffman pengaturan atas tubuh oleh struktur sosial yang berada di luar jangkauan diri/individu.[8]
Tubuh media ekspresi diri, yaitu sarana untuk bebas mengekspresikan semua yang ada di dirinya sendiri, apakah dalam bentuk perasaan, pikiran maupun ide-ide. Pilihan yang diambil untuk melakukan transisi, baik secara sosial maupun fisik oleh trans laki-laki adalah ekspresi tubuh yang seharusnya dimiliki oleh tubuh yang otonom. Namun, nyatanya masyarakat memiliki mekanismenya sendiri untuk mengatur tubuh. Tubuh privat tidak lagi menjadi tubuh yang otonom, namun menjadi tubuh yang terikat pada aturan dan sistem nilai yang telah terbentuk sebelumnya. Gail Weiss menekankan tentang identitas tubuh yang membedakan seseorang atau sekelompok orang lain. Ia juga menjelaskan tentang gagasan otonomi tubuh sebagai kemampuan seseorang untuk mengontrol tubuh mereka.[9]
Kebebasan tubuh yang otonom nyatanya menjadi gagasan yang probematis; di satu sisi, itu adalah hak mutlak bagi individu, tetapi di sisi lain kita tidak pernah mengetahui apakah setiap individu dapat benar-benar mengaksesnya. Namun, dalam masyarakat yang relatif komunal, arti ‘tubuh’ tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan dalam masyarakat individualistis, saklar tubuh, menandai batas-batas individu, yang adalah untuk mengatakan di mana dimulai dan berakhir kehadiran seorang individu.[10]
Tanggapan perusahaan terkait hal ini ditanggapi secara berbeda oleh trans laki-laki muda. Memilih untuk menjalani kerja di bidang informal akhirnya dipilih oleh beberapa informan sebagai bentuk negosiasi atas pilihan mereka untuk mempertahankan penampilannya yang maskulin. Namun, pilihan untuk tidak melakukan transisi fisik juga akhirnya diambil oleh informan lainnya sebagai pilihan rasional untuk tetap diterima bekerja di bidang pekerjaan yang ia minati. Di Indonesia, adanya aturan hukum ketenagakerjaan yang dengan jelas melarang praktik diskriminasi atas dasar apapun masih perlu dipertanyakan karena identitas gender ternyata masih menjadi dasar terjadinya diskriminasi dan ketidaksetaraan seksual. Oposisi biner yang berbasis konstruksi sosial masih menjadi dasar kuat yang menentukan status dan peran seseorang dalam dunia kerja.
[1] Cisfemale dan cismale (cis-gender) menjelaskan adanya keselarasan antara seks pada saat dilahirkan dengan identitas gender yang mereka yakini. Cisfemale adalah seseorang yang terlahir perempuan dan meyakini bahwa identitas gendernya juga perempuan sedangkan cismale adalah seseorang yang terlahir laki-laki dan meyakini bahwa identitas gendernya juga adalah laki-laki.
[2] Transgender pada umumnya didefinisikan sebagai individu yang dengan sengaja menolak penetapan gender yang diberikan pada saat lahir. Kelompok transgender adalah transseksual, namun melingkupi kelompok yang dapat lebih luas dari definisi ini. Catherine Connell, 2010, “Doing, Undoing or Redoing Gender? Learning from the Workplace Experience of Trangender People”, Gender and Society, Vol 24, 1, p. 33.
[3] Terminologi yang digunakan untuk menunjuk trans yang mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki (misalnya: seseorang yang terlahir sebagai perempuan namun mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki). Bahasanya lain yang digunakan adalah FTM (female to male). Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, United Nation Development Programme. 2015. Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia and the Pacific. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project.
[4] Hidup sebagai LGBT di Asia : Laporan Nasional Indonesia , Tinjauan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial Bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), diakses dari http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014_ID_FINAL_Bahasa.pdf
[5] Dalam wawancara yang dilakukan, informan penulisan ini mendefinisikan transisi sebagai proses ‘penegasan’ identitas mereka sebagai laki-laki. Transisi dapat dilakukan dalam bentuk transisi sosial, yaitu tidak melakukan penegasan fisik namun mengubah penampilan seperti laki-laki dan transisi fisik/medis, yaitu melakukan penegasan fisik melalui tindakan medis berupa HRT (Hormone Replacement Therapy). HRT adalah terapi yang dilakukan untuk meningkatkan kadar hormon testosteron dan menekan unsur hormon estrogen dalam tubuh.
[6] Konvensi-Konvensi ILO tentang Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Kantor Perburuhan Internasional, diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122045.pdf
[7] David Le Breton, La sociologie du corps, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 37.
[8] Chris Shiling, The Body and Social Theory, London, Sage Publication, p. 71.
[9] Gail Weis, 2009, “Intertwined Identities: Challenges to Bodily Autonomy”. Perspectives: International Postgraduate Journal of Philosophy, 2 (1) : 22-37.
[10] Le Breton, Loc.Cit., p. 34.